Kitab Tafsir Bercorak Linguistik: Tafsir al-Bahr al-Muhith Karya Abu Hayyan
Al-Qur’an menempati kedudukan yang sangat
tinggi dalam Islam, tidak hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai
petunjuk utama dalam kehidupan umat manusia. Kesakralannya mendorong umat untuk
lebih meresapi dan memahami isi al-Qur’an secara mendalam agar dapat
mengaplikasikan ajarannya dalam kehidupan.[1] Namun, pemahaman al-Qur’an yang tepat
membutuhkan penafsiran yang cermat oleh para mufassir dengan keilmuan yang
mendalam.
Fenomena penafsiran al-Qur’an tejadi sejak sejak
masa Nabi Muhammad Saw. dan mengalami perkembangan hingga saat ini.
Permasalahan yang semakin kompleks dari masa ke masa menuntut berkembangnya pendekatan
dalam menafsirkan al-Qur’an sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman. Di samping
itu, setiap mufassir memiliki latar belakang intelektual, sosial, dan
pengalaman yang memengaruhi sudut pandangnya dalam menyingkap setiap makna
al-Qur’an yang terkandung. Tidak heran ketika banyak dijumpai mufassir yang
berfokus pada hukum, teologi, kebahasaan, dan sebagainya.
Salah satu tokoh yang terkenal dengan pendekatan kebahasaan dalam tafsir adalah Abu Hayyan, melalui karyanya yang monumental, yaitu al-Bahr al-Muhith. Beliau dikenal sebagai seorang ahli bahasa dan sastra Arab sehingga berusaha menafsirkan al-Qur’an dengan menyingkap makna kata, kedudukannya, bahkan unsur sastra yang terkandung di dalamnya.[2] Dalam tulisan ini, penulis berusaha mengungkap latar belakang sosial dan keilmuan Abu Hayyan yang melatarbelakangi dominasi corak kebahasaan dalam karya tafsirnya. Selain itu, untuk membuktikan keabsahan klaim tersebut, penulis akan menguraikan dan menjelaskan metode penafsiran yang digunakan Abu Hayyan dalam kitab tafsirnya. Lebih lanjut, penulis juga akan menyoroti berbagai tanggapan dari para mufassir lain terhadap kitab ini, karena setiap karya tafsir, termasuk Al-Bahr al-Muhith, tidak terlepas dari kritik maupun apresiasi.
Biografi Pengarang
Kitab Tafsir al-Bahr al-Muhith ditulis oleh Abu
Abdillah Muhammad ibn Yusuf ibn ‘Ali ibn Yusuf ibn Hayyan al-Gharnathiy
al-Andalusiy, popular dengan sebutan Abu Hayyan, dan juga memiliki nama julukan
yaitu atsirudin. Nama al-Gharnathiy adalah tempat belajar
pertamanya sekaligus nama kota kelahirannya, yaitu Granada yang terletak di
wilayah Andalusia. Beliau dilahirkan di Andalusia pada abad ke-13,
tepatnya tahun 1256 M (654 H) dan menghembuskan napas terakhirnya di Mesir
pada abad ke-14, tepatnya tahun 1344M (745 H).
Abu Hayyan hidup dalam lingkungan keluarga
yang mendukung perkembangan dalam memahami Islam serta perkembangan
intelektualnya. Sedari kecil, beliau banyak mempelajari al-Qur’an baik
memahami, menghafal, serta mempelajari qiraatnya. Selain itu, Abu Hayyan telah
menunjukkan kegemaraanya terhadap bahasa karena pandai dalam membuat dan
menggubah syair-syair Arab. Ia sangat mengidolakan Sibawayh, tokoh nahwu. Awalnya beliau
berhubungan baik denan Ibnu Taymiyayah, dan menciptakan qasidahpujian untuknya.
Namun hubunan itu renggang karena Ibnu Tamiyyah banyak menyalahkan Sibawayh
dalam masalah tata Bahasa Arab.[3]
Setelah usia Abu Hayyan menginjak 25 tahun,
beliau banyak berkelana untuk menuntut ilmu dengan mendatangi beberapa ulama
terkemuka di berbagai belahan dunia. Diantaranya seperti wilayah Afrika,
Iskandaria, Hijaz dan Mesir. Abu Hayyan banyak berjumpa dengan para ‘alim
ulama’ dan berbagai tokoh yang terkenal untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang
luas. Adapun Mesir, menjadi wilayah di mana Abu Hayyan menetap dan menggunakan
sisa waktunya untuk menulis serta mengajar hingga akhir hayatnya.[4]
Karya-karya yang ditulis Abu Hayyan mencakup berbagai
bidang, seperti hadis, tafsir, bahasa Arab, qiraat, sastra, sejarah, serta nahwu
sharaf. Kekayaan karya ini mencerminkan hasil dari perjalanan panjangnya
menuntut ilmu dengan berbagai guru terkemuka, sebanyak 450 guru.[5] Diantara guru-guru besar tersebut adalah Ahmad ibn Ibrahim ibn Zubai ibn
Muhammad ibn Ibrahim sebagai seorang muhaddis, nahwiyyin (ahli nahwu), ahli
ushul fiqh, ahli sastra, serta fasih dalam memahami al-Qur’an. Al-Husain ibn
Muhammad Abd al-‘Aziz ibn Muhammad ibn Abd al-‘Aziz yang merupakan seorang
fuqaha, muhaddis, ahli nahwu dan sastra. Selanjutnya Ali ibn Muhammad ibn
Muhammad ibn Abd ar-Rahim, Muhammad ibn Ali ibn Yusuf, dan Muhammad ibn Ibrahim
ibn Muhammad yang merupakan ulama besar dari Mesir. Penyebutan para guru ini
menggambarkan betapa luasnya ilmu yang dikuasai Abu Hayyan di masanya.[6]
Abu Hayyan banyak menghasilkan karya yang
terkemuka dan bertebaran di berbagai penjuru dunia, baik selama hidup ataupun
setelah meninggal[7], diantaranya adalah:[8]
1. Al-Bahr al-Muhīth
2. Al-Nahr al-madd min Bahr al-Muhīth
(ringkasan dari kitab tafsir al-Bahr al-Muhīth)
3. ‘Aqdu Al-Lali ‘ala wazni al-Syātibiyyah
wa Qāfiyatihā.
4. Awali,Al-Khalil Khaliah fi Isnād Qirā’at
Al-Aliah.
5. Taqrīb Al-Nā’I fi Qirā’at Al -Kisā’i.
6. Al-Wahaj fi Ikhtisār Al-Minhaj.
7. Al-Anwār Al-Ajali fi Ikhtisār Al-Mahla.
8. Masāil Al-Rasyīd fi Tajrīd Masāil Nihāyah
Ibn Rasd.
Selain keahlian Abu Hayyan dalam berbagai
disiplin ilmu, para ulama juga banyak yang mengakui keilmuwannya, diantaranya:[9]
1. Imam Ibnu
Jazari mengatakan bahwa beliau adalah seorang hafizh, dan ulama besar di bidang
bahasa Arab, adab, qiraat, dan penguasannya yang tsiqoh.
2. Imam asy-syaukani
mengaatakan bahwa beliau adalah ulama yang sangat menguasai di bidang bahasa
Arab dan tafsir, di mana beliau merupakan pakar yang tidak dapat disamakan di
masanya,
3. Ibnu Qadhi
menulisnya di kitab thabaqot asyafi’iyyah bahwa beliau adalah seorang yang
hafizh, ahli nahwu, tafsir dan bahasa. Karyanya dikenal secara luas baik di
barat maupun timur.
Sejarah dan Latar Belakang Penulisan
Diantara karya-karya yang ditulis oleh Abu Hayyan, kitab tafsir Al-Bahr al-Muhīth menjadi yang
paling terkenal dengan jumlah 8 jilid. Kitab tersebut ditulis sejak berusia 57
tahun, tepatnya pada tahun 710 H, saat menjabat sebagai pengajar tafsir di Kubah
Sultan al-Malik al-Mansur. Di dalam karya tafsir ini, Abu Hayyan banyak merujuk
pada penafsiran al-Zamakhsyari dan Ibnu ‘Athiyyah, khususnya dari segi bahasa
sambil tetap memperhatikan aspek-aspek penting seperti asbabunnuzul, naskh
mansukh, qiraat, dan balagah, Walaupun cakupannya luas, Abu hayyan lebih
menonjolkan penjelasan seputar i’rab dan nahwu dalam menafsirkan ayat-ayat
al-Qur’an[10]
Sebagian besar karyanya berfokus pada bidang nahwu,
shorof, bahasa, fiqh, i’rab, dan qira’at. Semua disiplin ilmu ini terangkum
dalam kitab tafsirnya, Al-Bahr al-Muhīth, sehingga mencerminkan keluasan
ilmunya. Nama Al-Bahr
al-Muhīth berasal dari dua unsur kata, yaitu al-bahr dan al-muhīth.
Secara Bahasa, kata al-bahr artinya lautan, yang dalam konteks tafsir diartikan sebagai penyelaman ke
kedalaman makna. Sedangkan kata al-muhīth berarti segala sesuatu yang
mengelilingi lautan, melambangkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk menyelami
makna dan hikmah dalam al-Qur’an al-Karim.[11]
Dalam proses
penulisan tafsir bahrul Muhith Ini dilandasi oleh tiga hal, pertama: ia
berkeinginan selalu membaca al-Quran, kedua: beliau ingin memperbanyak amal
kebaikan, kemudian yang ketiga: Agar jiwanya selalu terjaga.[12] Melalui penamaan kitab ini, Abu
Hayyan berharap dapat menjelaskan makna setiap kata dalam
al-Qur’an secara detail serta mendalam. Beliau dalam tafsirnya menguraikan setiap ayat al-Qur’an secara mendalam
baik dari segi i’rab, bentuk-bentuk kata, susunan kalimat, hingga sisi kebahasaannya
kecuali bagian-bagian yang telah jelas maknanya. Selain itu, beliau juga
menjelaskan segi kemu’jizatan al-Qur’an melalui ilmu sastra dan
memberikan penafsiran dengan memadukan berbagai disiplin ilmu yang dimilikinya. Dengan pendekatan ini, Al-Bahr al-Muhīth menjadi
salah satu karya tafsir yang menggabungkan keluasan ilmunya dengan kedalaman
analisis terhadap al-Qur’an.[13]
Sumber, Metode dan Corak Penafsiran
Berkembangnya peradaban Islam bersamaan dengan munculnya berbagai macam
corak tafsir salah satunya yaitu corak Lughawy. Corak Lughawy yaitu menguraikan makna setiap ayat al-Qur’an dengan petunjuk atau kaidah kebahasaan.[14] Corak Lughawy merupakan corak yang digunakan Abu Hayyan, sesuai pemaparan
tafsirnya yang dituliskan dengan rinci. Dalam pendekatan ini, Abu Hayyan sering
mengutip penafsiran Az-Zamakhsyari dan Ibnu Athiyyah, dua mufasir yang juga
banyak menggunakan pendekatan bahasa dalam karya tafsir mereka.[15] Karya tafsirnya juga dianggap sebagai madrasah
lughawy dan Nahwu bagi siapa pun yang berkeinginan untuk memahami al-Qur’an
dengan bahasa Arab yang fasih. Salah satu muridnya yang mencapai kedudukan
sebagai imam besar dalam ilmu nahwu adalah Ibnu Hisyam al-Nahwi.[16] Berdasarkan corak yang digunakan Abu Hayyan, maka diambil kesimpulan bahwa
sumber penafsirannya didasarkan pada ra’yi.[17]
Selanjutnya, Penguraian tafsir ditempuh dengan menggunakan metode/manhaj tahlili.
Metode ini adalah cara penafsiran yang ditempub oleh para mufassir dalam menjelaskan makna setiap ayat al-Qur’an secara
berturut-turut dengan rinci dan lengkap.[18] Walaupun dalam perincian tafsirnya, beliau cenderung membahas terkait kebahasaan
yang terdapat di dalam setiap ayatnya.[19] Bahkan
kecenderungan ini mengantarkan pada anggapan bahwa kitab tafsir Al-Bahr
al-Muhīth lebih mendekati kepada kitab Nahwu daripada kitab tafsir.[20]
Abu Hayyan memisahkan penjelasan tafsirnya menjadi dua macam, yaitu
mufrodat dan tafsir. Pada bagian pertama, ia membahas seputar lafazh ayat.
Sedangkan pada bagian kedua, ia membahas makna dari suatu lafazh atau ayat.
Adapun Langkah-langkah penafsiran yang dilakukannya sebagai berikut:
1. Membahas kosa
kata ayat yang perlu diuraikan baik dari segi Bahasa maupun kedudukan kata pada
bagian awal penjelasan. Kemudian menggunakan syair Arab atau mencontohkan suatu
kalimat sebagai petunjuk memahami sebuah kata. Namun demikian, ada beberapa
bagian ayat yang tidak disertakan sebagaimana di dalam penjelasannya pada QS.
Ali Imran ayat 164.[21]
2. Menjelaskan
sebab turunnya ayat, naskh Mansukh, munasabah ayat, menyebutkan setiap qiroat
yang ada baik bacaan yang mutawatir maupun syadz, dan menukil perkataan nabi,
sahabat, dan tabiin dalam memahami maknanya. Dalam hal penyebutan qiroat syadz
di dalam tafsirnya, Abu Hayyan memberikan keterangan dan menjadikannya sebagai salah
satu alat bantu untuk menafsirkan sekiranya memiliki keterkaitan dengan ayat.[22] Abu Hayyan juga bersikap tegas dalam penukilan bacaan qiraat sebagaimana
kritiknya terhadap az-Zamakhsyari dan Abu Ubaid yang dianggap lebih
mengedepankan kaidah kebahasaan.
3. Beliau mahir
dalam Bahasa Arab sehingga menguraikan penjelasan I’rob yang memiliki kerancuan
di dalamnya. Selain itu, beliau juga merincinya dari segi balaghah baik badi’
ataupun bayan.
4. Menjelaskan
hukum syariat berkaitan dengan lafadz al-Qur’an berdasarkan Imam-imam arba’ah
(Imam Hanafi, Malik, Syafi’i, dan Hanbali) dan selainnya yang merujuknya kepada
kitab-kitab fiqh.[23]
Selain itu, ketika menemukan hukum-hukum yang
dianggap aneh dan menyelisihi pendapat mayoritas, Abu Hayyan melakukan tarjih
dengan menggunakan dalil-dalil yang diperlukan. Metode ini sebagai upayanya
dalam menjelaskan makna al-Qur’an dengan sebaik-baiknya karena al-Qur’an dianggap
sebagai kalam yang paling fasih. [24]
Kontroversi Karya Tafsir Abu Hayyan
Kitab tafsir al-Bahru al-Muhīth menuai berbagai kritik, baik dalam
perujukan pendapat, sanad, penisbatan hadits, dan sebagainya. Diantara kritik
yang didapatkannya yaitu:
1. Tidak merujuk
suatu perkataan kepada kitab aslinya
Abu Hayyan memiliki buku rujukan yang utama
dalam mengutip perkataan ahli Tafsir dan ini telah disebutkan secara jelas
dalam mukadimahnya yaitu kitab tafsir al-Kasyaf dan al-Muharrir al-Wajiz.[25] Di mana seharusnya, beliau mengutip suatu
pemikiran langsung kepada rujukan aslinya. Hal ini dapat menyebabkan kekeliruan
dalam memahami dan pengutipan suatu penjelasan. Kekeliruan tersebut ditemukan
dalam tafsirnya Qs. Al-Hijr ayat 88 yang berbunyi:
لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا
مَتَّعْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ
“Jangan
sekali-kali engkau (Nabi Muhammad) menujukan pandanganmu (tergiur) pada
kenikmatan hidup yang telah Kami berikan kepada beberapa golongan di antara
mereka (orang kafir)...”
Pada penjelasan ayat tersebut, Abu Hayyan
mengutip tafsir ar-Razi yang merujuk kepada pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas
mengatakan, “Janganlah mengharapkan kenikmatan duniawi yang telah diberikan
Allah kepada orang lain.” Pendapat ini juga disampaikan oleh Imam ath-Thabari melalui kitab tafsirnya yang merupakan imam yang lahir sebelum Abu Hayyan. Adapun kesalahan juga ditemukan dalam penukilan
pendapat mutaqaddimin melalui tafsir Ibnu Athiyyah di mana Abu Hayyan
dianggap melakukan wahm karena beliau menyebutkan suatu pendapat yang
disandarkan pada Ibn Athiyyah dari ath-Thabari yang pada kenyataannya tidaklah
demikian.
2. Terlalu banyak
menukil pendapat
Abu Hayyan seringkali berlebihan dalam menukil
pendapat sehingga ditemukan banyak pendapat yang sama secara makna walaupun
berbeda secara lafazh atau dapat dikatakan “Qoulun wahidun bi alfadzin
mutaqoribatin”. Sebagaimana penafsirannya dalam QS. Ali Imran ayat 117:
كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ
“…seperti perumpamaan angin yang mengandung hawa yang sangat
dingin”.
Pada penjelasan ayat tersebut, Abu Hayyan
menukil lebih dari satu pendapat yang memiliki kesamaan makna. Pertama,
disebutkan oleh Ibnu Kaisan berupa “suara api”. Dan yang kedua disebutkan oleh
az-Zajjaj bahwa kata “Shir” juga merupakan suara api yang tertiup angin.
Permasalahan ini banyak ditemukan di dalam
kitab tafsir al-Tahrīr al-Tahbīr karya Syaikh Ibn al-Naqīb yang merupakan kitab
rujukan Abu Hayyan. Sedangkan penjelasan dalam tafsir al-Tahrīr al-Tahbīr dianggap
terlalu bertele-tele dan banyak terjadi pengulangan yang tidak berguna.
3. Meringkas suatu
pendapat
Terkadang pula, Abu Hayyan sekedar
menyimpulkan suatu pendapat tanpa menukilnya secara utuh. Hal ini menyebabkan
pembaca harus merujuknya kembali kepada kitab pokoknya supaya dapat memahami
penjelasannya.
4. Terdapat Wahm
Sebagaimana beliau dalam menyebutkan periwayat
hadits mengenai mendengarkan bacaan al-Qur’an. Disebutkan bahwa faktanya,
perkataan itu hanya diriwayatkan oleh Said bin Musayyab namun beliau
menyebutkan Ibnu Mas’ud, Abu Hurairah, Jabir, Atha’, dsb.[26]
Contoh Penafsiran
Pada QS. Al-Fatihah ayat 1 akan terlihat bagaimana Abu Hayyan menguraikan
kata pertama dalam lafazh bismillah begitu kental dari segi bahasanya.[27] Dalam Huruf ba’ disebutkan memiliki berbagai macam makna, diantaranya
sebagai pelekat, permintaan tolong, sumpah, penyebab, keadaan, menunjukkan
tempat dan waktu, dan perpindahan. Kemudian menjelaskan setiap katanya ketika
digunakan di dalam kalimat.
Setelah melakukan penguraian dan penjelasan pada lafazh, beliau melakukan
pemilihan makna yang sesuai dengan ayat yang ditafsirkannya. Penjelasan
tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
[1] Nova Yanti, “Memahami Makna Muhkaman Dan Mutasyabihat
Dalam Al-Qur’an,” Al-Ishlah: Jurnal
Pendidikan 08, no. 02 (2016): 246–256.
[2] Ahmad Kamil Taufiq and Deswanti Nabilah Putri, “Telaah
Metodologis Kitab Tafsir Al-Bahr Al-Muhith Karya Abu Hayyan Al-Andalusy,” Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora 2, no.
1 (2023): 57–65.
[3] Saichul Anam, “Bayang-Bayang Ibnu ’Atiyah Dalam Tafsir
Al-Bahr Al-Muhith Karya Abu Hayyan Al-Andalusiy,” Qaf 06, no. 01 (2024): 59–78.
[4] M Rusydi Khalid, “Al Bahr Al-Muhîth: Tafsir Bercorak
Nahwu Karya Abu Hayyân Al-Andalusî,” Jurnal
Adabiyah 15, no. 2 (2015): 181–192.
[5] Romlah Widayati, Dimensi
Fiqh Abu Hayyan Dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhith, 2023.
[6] Miatul Qudsia, “Khazanah Keintelektualan Abu Hayyan
Dalam Samudera Ilmu Yang Luas” (2014): 327–328.
[7] Muhammad Hasdin Has, “Karakteristik Tafsir Al-Bahru Al
Muhith ( Telaah Metodologi Penafsiran Abu Hayyan Al-Andalusy ),” Shautut Tarbiyah vol 18, no (2012):
42–52.
[8] Elmia Zarchen Haq and Khoirul Umami, “Telaah Kitab
Tafsir Bercorak Lughawi Di Abad Pertengahan (Studi Komparasi Antara Tafsir
Anwar at-Tanzil Wa Asrar at-Ta’wil Fi at-Tafsir Dan Al-Bahr Al-Muhit),” Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan
tafsir 02, no. 01 (2022): 50–65.
[9] M.Atho’ Illah Hikam et al., “Implikasi Ayat Kursi
Menurut Abu Hayyan Al-Andalusi Dalam Kitab Bahr Al- Muhit Fi Al- Tafsir,” Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan
Multikulturalisme Indonesia 1, no. 2 (2023): 104–114,
[10] Abu Hayyan, Al-Bahr
Al-Muhith, Jilid 1. (Damaskus: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 1435). Hal. 45-46
[11] Restu Ashari Putra and Andi Malaka, “Manhaj Tafsir
Bahrul Muhith Abu Hayyan Al-Andalusiy,” Jurnal
Iman dan Spiritualitas 2, no. 1 (2022): 91–96.
[12] Abu Hayyan, Al-Bahr
Al-Muhith, Jilid 1. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). Hal. 5
[13] ‘Amilatu Sholihah, “Analisis Ibdal Dalam Al-Qur’an
Perspektif Abu Hayyan Al-Andalusia an-Naysaburi Dan an-Nasafi,” Profetika: Jurnal Studi Islam 1, no. 9
(2020): 195–211.
[14] Widayati, Dimensi
Fiqh Abu Hayyan Dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhith.
[15] Muchammad Fariz Maulana Akbar and Muhammad Rijal
Maulana, “Kajian Historisitas Tafsir Lughowi,” Jurnal Iman dan Spiritualitas 2, no. 2 (2022): 239–246.
[16] Has, “Karakteristik Tafsir Al-Bahru Al Muhith ( Telaah
Metodologi Penafsiran Abu Hayyan Al-Andalusy ).”
[17] Hayyan, Al-Bahr
Al-Muhith. Hal. 11
[18] Nashruddin Baidan, Wawasan
Baru Ilmu Tafsir, Cetakan IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021). Hal. 376
[19] Has, “Karakteristik Tafsir Al-Bahru Al Muhith ( Telaah
Metodologi Penafsiran Abu Hayyan Al-Andalusy ).”
[20] Widayati, Dimensi
Fiqh Abu Hayyan Dalam Tafsir Al-Bahr Al-Muhith.
[21] Muhammad Husein Adz-Dzahabi, Tafsir Walmufassirun, vol. Jilid 1 (Mesir: Maktabah Wahbah, n.d.). Hal. 226
[22] Hayyan, Al-Bahr
Al-Muhith. Hal 26
[23] Ibid. Hal.10
[24] Abu Hayyan, Al-Bahru
Al-Muhith, Jilid 1. (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). Hal. 6. Maktabah
Syamilah
[25] Hayyan, Al-Bahr
Al-Muhith. Hal. 10
[26] Ibid. Hal. 39
[27] Abu Hayyan, Bahr
Muhith, Jilid 1. (Damaskus: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, n.d.). Hal 26-34
[28] Putra and Malaka, “Manhaj Tafsir Bahrul Muhith Abu
Hayyan Al-Andalusiy.” Hal. 93
Penulis:
Hanifah As Sa'diyah Jannati (email: hanifahjannati21@gmail.com)
Rahma Aulia Irmawati
(Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, UIN Surakarta)
Pembimbing:
Prof. Dr. KH. Moh Abdul Kholiq Hasan, Lc., M.Ag., M.Ed
.jpeg)

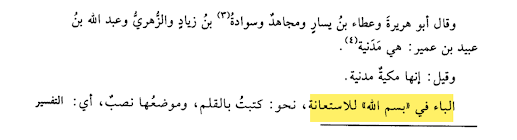

Komentar
Posting Komentar